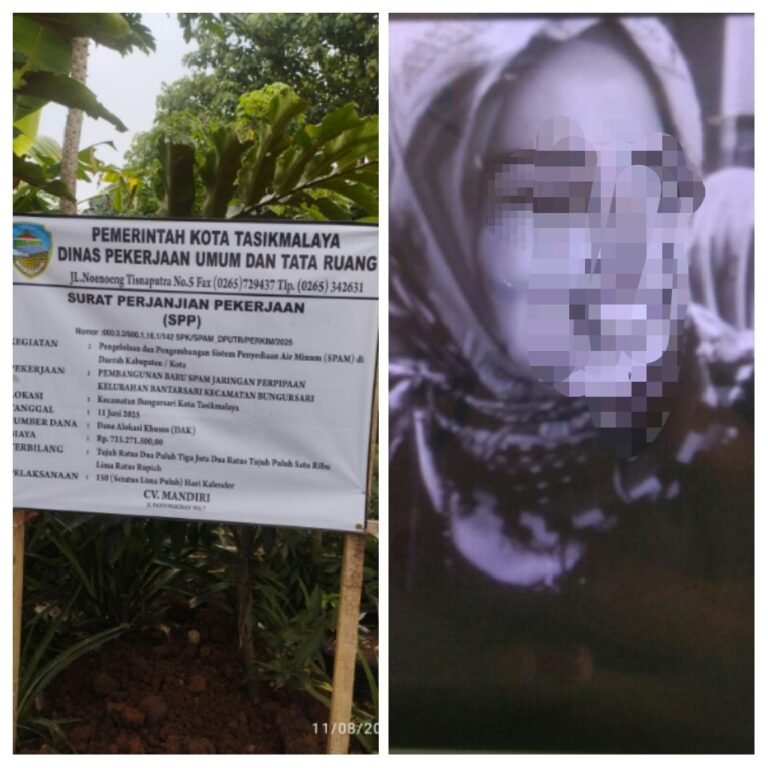Jakarta, (Patroli Indonesia). Kasus-kasus intoleransi di Indonesia bagian barat, khususnya di Pulau Sumatera dan Jawa, masih menjadi isu krusial yang kerap muncul ke permukaan. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, realitas di lapangan menunjukkan bahwa gesekan antarumat beragama dan kelompok etnis masih sering terjadi, bahkan terkesan dibiarkan atau belum ditangani secara tuntas dan menyeluruh oleh pihak berwenang. Demikian simpulan atas tinjauan perkembangan mutakhir dalam bedah perkara berbangsa, yang diselenggarakan FORMANAS (Forum Organisasi Massa Nasionalis), AWPN (Asosiasi Wartawan Peta Nusantara), YGL-Youth Gibran Lovers, GNP TIPIKOR RI, AWP (Aliansi Wartawan Pasundan), LOGISTRA (Locus Goverment Institute Studies Strategic), serta beberapa pakar dari beberapa perguruan tinggi dan ormas lainnya, di Sekertariat Patroli Indonesia Wilayah Barat.
Simpulan yang lebih rinci, antara lain sebagai berikut. Bentuk dan Pola Intoleransi di wilayah barat Indonesia seringkali bermanifestasi dalam berbagai bentuk, meliputi: Pertama, Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah: Ini adalah salah satu bentuk intoleransi yang paling sering terjadi. Kasus penolakan pembangunan gereja, vihara, atau rumah ibadah agama minoritas lainnya dengan dalih perizinan atau penolakan warga sekitar masih terus ditemukan. Contohnya, kasus pelarangan pembangunan gereja di Cilegon, Banten, atau penutupan rumah ibadah di sejumlah daerah di Jawa Barat yang seringkali berlarut-larut.
Ke dua, Diskriminasi dan Intimidasi Terhadap Kelompok Minoritas: Anggota kelompok minoritas, baik agama maupun etnis, kerap mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan mendapatkan pelayanan publik, penolakan sosial, hingga intimidasi fisik atau psikis. Hal ini terlihat dari laporan-laporan Komnas HAM atau lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti perlakuan terhadap jemaat Ahmadiyah, Syiah, atau kelompok penghayat kepercayaan. Ke tiga, Aksi Kekerasan Berbasis SARA: Meskipun tidak selalu bersifat masif, aksi kekerasan yang dipicu oleh sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan masih terjadi. Konflik kecil antarwarga yang berujung pada perusakan fasilitas umum atau rumah ibadah juga menjadi catatan kelam. Ke empat, Penyebaran Ujaran Kebencian dan Provokasi: Media sosial dan platform daring seringkali menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu ketegangan antarumat. Konten-konten yang mendiskreditkan agama atau kelompok tertentu kerap beredar tanpa kontrol yang efektif.
Faktor-faktor Penyebab dan Kesan Pembiaran. Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi pemicu maraknya kasus intoleransi di Indonesia bagian barat: Pertama, Lemahnya Penegakan Hukum: Salah satu kritik utama adalah lambatnya atau bahkan absennya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku intoleransi. Kasus-kasus yang dilaporkan seringkali tidak diproses secara transparan atau berakhir tanpa kejelasan. Hal ini menimbulkan kesan impunitas bagi para pelaku dan tidak memberikan efek jera. Ke dua, Peran Aktor Non-Negara: Kelompok-kelompok intoleran atau organisasi masyarakat tertentu seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan mampu memobilisasi massa untuk melakukan aksi penolakan atau intimidasi. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menindak kelompok-kelompok ini memperparah situasi.
Ke tiga, Interpretasi Agama yang Eksklusif: Adanya pemahaman agama yang sempit dan merasa paling benar seringkali menjadi akar permasalahan. Hal ini mendorong sikap tertutup dan penolakan terhadap perbedaan. Ke empat, Minimnya Edukasi Keberagaman: Kurangnya pendidikan tentang pluralisme, toleransi, dan nilai-nilai kebhinekaan sejak dini di tingkat keluarga dan sekolah turut berkontribusi pada tumbuhnya bibit intoleransi. Ke lima, Kepentingan Politik Lokal: Dalam beberapa kasus, isu intoleransi juga ditunggangi oleh kepentingan politik lokal, terutama menjelang pemilihan umum, di mana isu SARA kerap dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ke enam, Kesan bahwa kasus-kasus intoleransi “dibiarkan” muncul karena seringkali pemerintah daerah atau pusat terkesan ragu-ragu dalam mengambil sikap tegas. Mediasi yang berlarut-larut tanpa hasil konkret, atau kecenderungan untuk mengakomodasi tekanan dari kelompok mayoritas, justru memperkuat narasi pembiaran ini.
Dampak dari intoleransi ini sangat merugikan: Pertama, Pecahnya Kohesi Sosial: Intoleransi merusak ikatan sosial antarwarga dan menciptakan kecurigaan serta permusuhan. Ke dua, Gangguan Keamanan dan Stabilitas: Kasus intoleransi dapat memicu konflik dan mengancam stabilitas keamanan di suatu daerah. Ke tiga, Pelanggaran HAM: Hak-hak asasi warga negara, terutama kelompok minoritas, seringkali terlanggar akibat praktik intoleransi. Ke empat, Citra Indonesia di Mata Internasional: Kasus-kasus intoleransi juga dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang plural dan demokratis. Ke lima, Menyikapi permasalahan ini, tantangan yang dihadapi sangat besar, memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi akar masalah dan menegakkan prinsip-prinsip toleransi secara konsisten. Tanpa penanganan yang tuntas dan menyeluruh, kasus intoleransi akan terus menjadi borok yang menghambat kemajuan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Mari kita semua segera bermawas diri, dan memperbaiki. (BHS-001)***